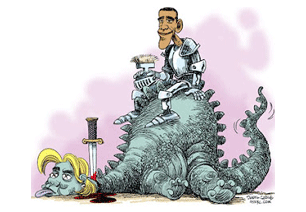|
| Jadud Sumarno |
Darminto M Sudarmo – (Buku)
Anatomi Lelucon di Indonesia , Kompas, 2004
PEPATAH lama mengatakan, koran/majalah tanpa karikatur ibarat sayur tanpa garam; hambar. Apakah itu berarti karikatur sejenis makhluk yang berasa asin? Tentu tidak. Karikatur itu sejenis tajuk rencana dalam bentuk gambar lucu. Kalau tajuk rencana menggambarkan sikap serius suatu penerbitan terhadap berbagai peristiwa atau tokoh yang sedang in atau menjadi bahan pembicaraan ramai masyarakat, maka karikatur bersikap secara beda; yakni, memberi isyarat-isyarat bahaya yang mungkin akan terjadi di masa depan sambil menyentil pihak-pihak tertentu dengan gayanya yang khas, lucu.
Cara ini cukup ampuh untuk mengajak pembaca merenungi persoalan sejenak dan kemudian di ujung perenungannya itu, biasanya pembaca akan menemukan sesuatu yang terungkap dalam bentuk senyum simpul atau ledakan tawa sebagai reaksi atas pemahamannya pada masalah yang ditawarkan kartunis.
Dengan kata lain, ibarat orang memberi pil pahit pada seseorang, kalau disertai segelas air, tentunya pasti lebih mudah ditelan. Begitu pula dengan kritik, akan efektif bila disampaikan dengan kemasan yang santai dan berbumbu humor. Itulah tugas utama seorang kartunis atau lebih spesifik: karikaturis.
Karikaturis yang baik, umumnya mampu mengeliminasi sebuah fakta yang ruwet dan kacau-balau menjadi sesuatu yang sederhana dan mudah dipahami, terutama lewat coretan gambarnya yang sangat ringkas; yakni, cuma satu kotak. Bayangkan, hanya satu kotak namun dapat mengungkap suatu cerita secara lengkap dan rampung.
Sementara itu, dalam hal meng-obok-obok substansi persoalan, karikaturis biasanya juga tangkas meragakan arogansi yang kenes, ignoransi yang naif, kesenjangan antara kata dan perbuatan, redukalisasi pernyataan oleh kenyataan, sembunyinya kesejatian wajah di balik kedok, kebengongan menghadapi yang absurd, kejelian menemukan dusta di balik kata-kata dan lain sebagainya. Setidaknya itu yang pernah disinyalir oleh Prof. DR. Fuad Hassan yang punya perhatian cukup istimewa terhadap humor dan kartun.
Dari seluruh kerja karikaturis (editorial/political cartoonist) yang tampaknya sederhana dan tinggal corat-coret itu, ternyata tidak sesederhana yang diduga orang. Minimal, ia harus punya bekal wawasan jurnalistik yang memadai; melek pengetahuan tentang masalah sosial, politik, ekonomi, hukum, kebudayaan, pertahanan dan keamanan. Khusus di negeri kita, karikaturis juga musti melek juga soal SARA (suku, agama, ras dan antargolongan); sesuatu yang sangat peka dan rentan masalah, bila tak pandai-pandai menyiasati. Masih belum cukup; karikaturis ternyata harus pintar mengemas kritiknya dalam suasana yang lucu atau jenaka; ini penting, untuk menghindarkan diri dari kecenderungan main vonis terhadap figur tertentu. Atau paling tidak, terhindar dari sikap insinuatif dan provokatif. Sehingga karyanya jadi tak beda dengan sebuah poster.
Apa jeleknya, poster? Karikatur memiliki “ideologi” yang lugas; yakni, bebas dari pretensi menghakimi; ia hanya memberikan isyarat-isyarat bahaya yang mungkin akan terjadi (It’s just early warning). Poster sebaliknya, menolak atau menyetujui sesuatu langsung pada persoalan, karena biasanya ia menjadi alat propaganda. Pendek kata, karikatur tanpa kontemplasi bakal terjerembab ke wilayah poster, yang parameter kualitas dan independensinya sudah jelas-jelas, sangat berbeda.
Di sisi lain, belum banyak orang mengerti, bahwa suka-duka karikaturis juga banyak; terutama di rezim Orde Baru; saat itu, begitu kompleks rambu-rambu larangan yang harus dicermati. Selain tidak boleh menyinggung SARA, juga tidak boleh menyinggung Keluarga Cendana, ABRI dan institusi-institusi lain yang dianggap peka.
Bisa dibayangkan, seperti apa produk karikatur yang muncul pada periode represi semacam itu? Untunglah, Megawati dengan PDI-nya pada periode itu, berada di posisi yang disakiti dan dipinggirkan, sehingga bukan sesuatu yang aneh bila sikap pers, secara diam-diam dan agak malu-malu, berupaya “membela” dan “bersimpati” pada Megawati. Ini sesuai moral pers, membela kaum yang lemah dan ditindas penguasa. Tak terkecuali, para karikaturis juga bersikap serupa. Dan sejumlah karikatur yang muncul di buku ini, diangkat dari November 1993 hingga tahun 1999, tampak nuansa yang menggambarkan proses itu.
Demikian alakadar pengantar sekilas untuk membantu pembaca agar dapat memahami bagian kecil dari keunikan cara berpikir dan bersikap para karikaturis. Dan supaya pemahaman pembaca makin lengkap dan kaya, berikut disajikan opini para kartunis terhadap profil seseorang yang sangat penting dan bakal merangkai sejumlah sejarah penting di negeri ini. Siapa lagi tokoh itu, kalau bukan Megawati Soekarnoputri dengan PDI Perjuangan-nya. Ini dia, kesan dan pesan mereka.
(Tentu saja komentar para kartunis berikut diungkap beberapa waktu sebelum Megawati menjadi Presiden RI-penulis).
GM SUDARTA, Harian Umum KOMPAS
Dikuya-kuya. Kalau harus berpihak, di manakah keberpihakan kartunis? Sementara kita beranggapan, kartunis itu berdiri di luar pagar; sebagai pengamat, sebagai anjing penjaga yang siap menyalak apabila ada sesuatu kecurigaan terhadap sesuatu yang tidak beres.
Kami rasa, memang kartunis harus berpihak; yakni berpihak kepada Hti Nurani Kebenaran dan Keadilan serta Hukum yang dipermainkan oleh penguasa untuk membodohi rakyat dan memojokkan Mbak Mega.
Simpati dan rasa hormat kami kepada Mbak Mega yang banyak diam dan tersenyum , meskipun telah “dikuya-kuya”. Kami yakin Mbak Mega, bahwa “Wani ngalah iku dhuwur wekasane”.
PRAMONO R. PRAMOEDJO, Harian Sore SUARA BANGSA
Sebagai seorang tokoh politik yang kharismatik, Megawati Soekarnoputri, yang lebih banyak diam daripada bicara secara terbuka itu, tampaknya cukup puas dengan begitu besarnya dukungan masyarakat terhadap dirinya dan PDI Perjuangan. Dukungan yang terang-terangan, terbuka, maupun yang diam-diam dan samar. Dukungan yang didasari akal budi dan realitas kebenaran, maupun yang emosional atau sekadar ikut-ikutan.
Saya yakin, Mbak Mega pasti sudah diingatkan oleh para penasihatnya soal bahayanya ranjau “puas diri” itu; yang jika tidak disadari dan diredam akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri.
Sebagai seorang kartunis, saya pun mengamati fenomena PDI dan Megawati; sejak KLB di Surabaya, 1993; Kongres di Medan dan bahkan, sebelumnya. Yang saya ketahui, putri Bung Karno ini memang terkesan “dingin” jika dibandingkan dengan mendiang ayahnya, yang “panas” itu. Sebenarnya, jenis wejangan dan pelajaran atau falsafah apa yang diterimanya sih, sehingga terkesan dingin tapi tidak arogan itu.
Mbak Mega dan Partai Demokrasi Indonesia bagi rakyat Indonesia ibarat “mimi lan mintuno”, tidak terpisahkan. PDI ya, Mega, Mega ya, PDI! Begitu kata orang. Meski diobok-obok , digoyang-goyang, bahkan digunting dalam lipatan, Megawati Soekarnoputri tetap teguh, tegar; atau jangan-jangan malah, cuek!
Keinginan rakyat saat ini agar Mega berbicara di depan umum tentang jalan pikirannya perihal negeri ini dengan program-programnya ke depan, mungkin sama dengan kegilaan saya untuk mendengarkan setiap kata dan kalimat yang diucapkan Bung Karno dalam setiap pidatonya yang disiarkan di radio. Jadi, tunggu apa lagi, Mbak?
Sebagai seorang kartunis, sudah sejak lama saya pun ingin menggambarkan fenomena Mega ini ke dalam karya-karya saya secara utuh, lugas dan transparan permasalahannya. Namun, kita semua tahu, zaman Orde Baru, boleh dikatakan mengemukakan pendapat secara bebas dan jujur itu barang mahal dan berbahaya. Tapi, di situlah tantangannya. Jika terang-terangan sulit ditembus, maka masih ada cara dan jalan lain “menuju Roma”. Bukan asal jadi, namun suatu karikatur yang “halus bak sutera” sehingga tidak begitu mudah dicerna; memang itu memerlukan kreativitas yang tinggi. Yang ketika dituangkan ke dalam gambar karikatur masih memerlukan suatu “filter” yang membuat karya itu berhenti pas, pada suatu garis yang aman. Aman bagi surat kabar yang memuatnya, aman bagi seluruh karyawan penerbitan, dan utamanya aman…bagi saya!
Alhasil, karikatur-karikatur yang secara tegas dan jelas memajang Megawati Soekarnoputri yang harusnya dibela (salah satu misi karikatur adalah membela yang benar namun terpojok), akan berkonotasi ikutan memojokkan Mega, atau bahkan karikatur bertemakan PDI dan Mega sangat jarang muncul; lantaran pimpinan redaksi surat kabar bersangkutan berkeberatan memuatnya dengan alasan: keamanan.
Sekian dulu, terpaksa saya hentikan, soalnya saya diburu untuk segera menggambar karikatur.
PRIYANTO S. Majalah Berita Mingguan TEMPO dan D&R
Mega seangkatan denganku waktu SMA. Cuma, dia di SMA Cikini, aku di Kanisius. Kadang penasaran juga main ke Cikini naik sepeda mau tengok puteri presiden. Naksir sih, tak berani; meski Bung Karno pernah menawarkan siapa pun boleh melamar Mega, saat ramai-ramainya kampanye sukarelawan Dwikora.
Waktu itu penampilan Mega sederhana banget. Boleh jadi hasil didikan ibunya, Bu Fatmawati yang orang Sumatera Selatan itu. Dan memang saat itu belum musim anak presiden jadi konglomerat.
Nama Mega baru ramai lagi sejak tiba-tiba Kongres PDI (seperti biasa) ricuh dan orang ribut cari Mega buat ketua penengah. Selanjutnya perjalanan Ibu Mega kita sudah kita ikuti bersama. Juga selanjutnya kesanku tak beda dengan kebanyakan orang; ia tetap sederhana.
Kelihatannya beliau suka mendengar dan membimbing, kurang suka meracau dan tak ambisius. Yang meributkan beliau jadi presiden kan orang-orang…Ibu Mega sih, diam saja. Betul begitu kan, Bu?
M. NAJIB, Harian RAKYAT MERDEKA
Pemilu kemarin kalau nggak salah, diikuti oleh 48 partai; tapi, sepertinya hanya ada 2 (dua) partai saja yang bertarung; yakni, PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Sebagaimana kita semua tahu, PDI Perjuangan dengan Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri di masa Orde Baru selalu dikerjain oleh Rezim Soeharto. Sedangkan Partai Golkar adalah kendaraan politiknya BJ Habibie, yang pernah mengaku murid daripada Soeharto.
Kenapa PDI Perjuangan bisa mengungguli perolehan suara dari partai lain, termasuk Golkar yang di masa lalu, tiap Pemilu selalu menang sebelum perhitungan suara dilakukan? Karena bagi rakyat banyak PDI Perjuangan merupakan wadah untuk mengekspresikan kemuakan orang terhadap Rezim daripada Soeharto. Ingat 27 Juli 1996 adalah suatu momentum penting yang akhirnya “menobatkan” Megawati sebagai korban yang di-kuyo-kuyo oleh Orde Soeharto.
Jadi ketika kemuakan terhadap Rezim Soeharto semakin memuncak, sosok Megawati yang semula menjadi korban lantas muncul sebagai alternatif.
Anehnya, kenapa Rezim daripada Soeharto takut terhadap Megawati yang jelas hanya seorang wanita ramah, keibuan dan agak pendiam itu? Atau jangan-jangan khawatir dengan kursinya?
Dengan bukti kemenangan PDI Perjuangan dalam Pemilu 1999, wajar toh bila pendukung Megawati berharap ia jadi presiden. Tapi, kata orang-orang pinter yang ngatur negara, di Indonesia, Pemilu adalah pemilihan wakil rakyat, bukan pemilihan presiden.
Nah, ternyata di masa reformasi ini pun, Megawati masih juga diganjal oleh pihak-pihak pro-status quo; bahkan Majelis Ulama Indonesia ikut-ikutan mengeluarkana fatwa bahwa wanita tidak bisa menjadi pemimpin/presiden. Lho, katanya negara demokrasi, kok masih ada perbedaan antara laki-laki dan wanita? Padahal, syarat jadi presiden harus dipercaya oleh rakyat mayoritas; dan Pemilu sudah membuktikan itu. Misalnya yang menjadi presiden bukan Megawati, dilihat dari jumlah suara, jelas tidak mencerminkan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat.
Ada anekdot yang berkembang di masyarakat luas.
Presiden pertama, suka wanita.
Presiden kedua, takut wanita.
Presiden ketiga, kewanita-wanitaan.
Presiden keempat, wanita beneran!
NON-O S. PURWONO, Tabloid TOKOH, PERSPEKTIF dan lain-lain.
Megawati adalah figur dari simbol demokrasi. Bahwa ia adalah manifestasi dari “Ibu bagi rakyat jelata” atau “Wanita santun yang selalu memilih diam” atau “Wanita baja yang senantiasa tertindas oleh Monster Politik bertangan besi” adalah gambaran yang khas bagi Megawati.
Bagi saya, Megawati adalah simbol perjuangan yang tak kunjung henti. Ulet, pantang menyerah, senantiasa berjuangan tanpa kekerasan – tak terkecuali ketika suasana kekerasan sedang menjadi kebutuhan hidup sehari-hari – Megawati toh tampil dengan pola pandangan perjuangan seperti Mahatma Gandhi, Ahimsa. Anti kekerasan.
Megawati, selalu tampil sejuk di setiap kesempatan; di tengah-tengah rakyat yang haus kelembutan karena kegerahan suasana politik dan kekerasan; inilah yang membuat rakyat bak menemukan sebuah oase di tengah padang pasir. Ini pula yang membuat Megawati tampil menjadi semacam tempat berteduh bagi rakyatnya.
Ia menjadi semacam idola yang muncul pada saat bangsa Indonesia sedang dilanda krisis kepemimpinan selama 30 tahun lebih. Selama ini rakyat bagai kehilangan panutan. Kemunculan Megawati sebagai idola bagi saya seakan seperti rakyat Indonesia yang semula kehilangan kepercayaan dirinya untuk bertindak, bersikap maupun berbicara; lalu berubah menjadi bangsa yang menemukan kembali kepribadian aslinya.
Barangkali menarik menyitir ucapan Henry Kissinger yang mengatakan, “Intelligence is not all that important in the exercise of power, and is often, in point of fact, useless.” Akal bukanlah hal yang paling penting dalam menjalankan kekuasaan, dan dalam kenyataannya, sering tidak ada gunanya. Dalam beberapa hal, Megawati sangat tepat menjalankan perjuangannya dengan melihat pada hati nurani, bukan pada akal semata.
Lihatlah, hati nurani sekarang ini menjadi “barang mewah” bagi penguasa politik yang mengaku sebagai wakil rakyat atau pembela rakyat. Bagaimana dapat mengerti hati nurani rakyat kalau di tengah-tengah krisis yang sedang melilit bangsa Indonesia, masih banyak dijumpai pejabat yang dengan enaknya memakan uang suap. Di tengah-tengah rakyat yang kelaparan masih ada berita pejabat yang menilep bantuan uang hak para petani, korupsi di berbagai instansi, pejabat penegak hukum yang menerima uang sogok dan sebagainya.
Bagaimana bisa dikatakan mengerti hati nurani rakyat kalau kepentingan pribadi dan kelompok lebih diutamakan daripada kepentingan rakyat? Seluruh rakyat Indonesia tahu semua kejadian itu di depan hidungnya. Mbak Mega, panggilan akrab Megawati, pun juga tahu; terutama tahu hati nurani rakyat Indonesia.
Satu hal yang sangat kita harapkan, hendaklah Megawati selalu konsisten dengan perjuangannya; yakni, membela kepentingan rakyat. Menurut saya, beliau tahu persis apa yang dimaksud dengan suara hati nurani rakyat itu; karena apa yang dialaminya selama ini adalah cerminan dari penderitaan rakyat. Dan seorang ibu lebih banyak menggunakan naluri keibuan dan hati nurani dalam mengasuh “anak-anak”-nya; apalagi, anak-anaknya selama ini haus kasih sayang, kelembutan dan keteduhan.
Tampilnya Megawati ke pentas politik Indonesia, barangkali merupakan siklus alam yang tak dapat dihambat dengan cara apa pun. Terbukti dengan berbagai rekayasa penjegalan dirinya, yang tak kunjung mempan jua; bahkan, Mega tampil makin perkasa. Ia figur yang telah lolos dari ujian berat Kawah Candradimuka dan mampu keluar dengan tetap tegak, berwibawa dan dicintai rakyat.
Silence is a friend who will never betray. Diam adalah sahabat yang tak pernah berkhianat.
Mega, Yesss!
JITET KOESTANA, Tabloid SENIOR
(Aksen anak kecil)
Balu-balu ini di Jawa Timul, belulang lagi kejadian cap jempol dalah yang menghebohkan itu. Maka, komental pun langsung belkembang meliah, sepelti pasal malam. Ada yang menentang, ada yang mengklitik, ada yang menggului, ada pula yang mencemooh. Sebelumnya, kejadian yang sama juga teljadi di Semalang, Jawa Tengah. Sekital 3.000 walga PDI Plo-Megawati mengambil alih kantol DPP PDI di Jalan Bligjen Katamso 24. Meleka malah kalena Soemalyo, Ketua DPD Jawa Tengah mendukung pelencanaan Kongles di Medan. Massa PDI Peljuangan kemudian membubuhkan cap jempol dengan dalah di atas kain dan keltas yang belisi dukungan telhadap Ibu Mega. Komental banyak olang sih, menggelikan.
Tapi, bukankah pelistiwa 27 Juli 1996 tidak lebih menggelikan?Ail kobokan yang tadinya putih belsih, sekalang sudah belwalna melah kehitaman oleh dalah. Hingga mengalili ke selokan-selokan yang juga, belubah menjadi melah; kalena saking banyaknya olang-olang yang “cuci tangan” dengan masalah itu. Komental saya sih, sedelhana saja, “Lakyat tidak mau lagi dibohongi,”
Pemilu telah bellangsung dengan teltib, aman dan juldil. Lakyat dengan antusias menyelahkan suala dan menentukan pilihan meleka. PDI Peljuangan pun melaih suala telbanyak. Akankah suala sebagian besal lakyat yang telah diselahkan kepada PDI Peljuangan dan mendambakan telpilihnya Ibu Megawati menjadi Plesiden Lepublik Indonesia itu dileka-leka? Kulang cukupkah membohongi lakyat selama 32 tahun? Biallah lakyat belajal menikmati dan atau menanggung konsekuensi pilihan meleka. Biallah lakyat juga menikmati sebuah ketidakbohongan yang meleka dambakan.
Saat ini, saya kila, sebagian besal lakyat Indonesia sudah tidak punya lagi ail mata. Tangis meleka pun sudah tidak lagi mengelualkan bunyi. Bialkanlah sebagian besal lakyat Indonesia mendambakan belaian kasih dan dekapan cinta seolang Ibu. Pendek kata, meleka sangat belhalap agal Ibu Megawati menjadi Plesiden Lepublik Indonesia. Itu saja.
Semoga Indonesia yang selama 32 tahun panas menyengat, belubah menjadi teduh oleh mega-mega yang belhambulan; melindungi kita dali panas matahali. Dan ail kobokan tidak lagi belwalna melah kehitaman oleh dalah. Ail selokan, sungai juga tidak belwalna melah kehitaman kalena limbah kobokan yang beldalah tadi.
Salam dali Si Kecil Jitet Koetana yang tetap setia jadi kaltunis.
KOESNAN HOESIE, Harian Sore WAWASAN
Buat saya Mbak Mega itu sama halnya dengan wanita lainnya; seperti misalnya Mbakyu saya, ibu saya. Kehidupan yang membuat Mbak Mega tidak seperti lainnya, karena dia anak bekas Presiden negara ini, tinggalnya di Jakarta dan lain-lainnya. Apalagi, sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, sebuah partai yang pengikutnya sangat besar; terang saja Mbak Mega lalu menjadi sangat berbeda.
Saya tidak ingin warga Banteng punya fanatisme yang kadang sampai di luar nalar. Semoga di bawah pimpinan Mbak Mega mereka bisa dibawa ke arah situasi yang lebih cerdas, secerdas Pak Kwik Kian Gie, misalnya. Terus terang saya bersimpati pada PDI Perjuangan dan Mbak Mega, karena ada Pak Kwik di partai tersebut.
Terpaksa, saya tidak pakai cap jempol darah; maklum saya masih bisa bikin tanda tangan atau paraf pakai pulpen saya, gitu. Pokoknya, saya senang melihat Mbak Mega jadi presiden karena saya tidak senang melihat satu orang berkuasa terus-terusan; njelehi (menyebalkan), deh, pokoknya.
PRIE GS, (d/h) Harian SUARA MERDEKA (CEMPAKA MINGGU INI)
Megawati menjadi figur yang luar biasa, terutama, karena ia memiliki sesuatu yang orang lain tak punya; yakni: derita!
Benar, bahwa dia anak Bung Karno, tapi lain anak Bung Karno, lain pula derita yang dimilikinya. Mega memiliki akumulasi paling lengkap antara derita politik dan kharisma bapaknya.
Pengertian itulah yang membuat Mega tumbuh menjadi figur yang fantastik. Inilah figur dari sedikit tokoh di Indonesia yang dinaungi bakat primordialistik, simbolik dan “mistik”.
Karena itulah, sebetulnya Mega tak perlu kampanye untuk memenangkan Pemilunya. Massa Mega adalah massa yang sudah terbentuk sejak lama. Kepadanya tinggal dibukakan pintu yang lama dikunci paksa, untuk kemudian massa itu akan ber-euforia sedemikian rupa, memenuhi kehausan sosio-politiknya.
Mega saat ini, adalah tokoh yang tengah memanen sejarahnya. Dalam momentum semacam itu, mustahil bila ada upaya untuk menahan laju perjalanannya. Kalaupun tipuan politik sesekali menjatuhkannya, Mega yang sesungguhnya sulit untuk benar-benar jatuh.
WAWAN BASTIAN, Tabloid AURA
Bergunjing tentang Megawati serasa tak mengenal kata bosan. Bukan saja sejak rezim Orde Baru merajalela, bahkan sampai sekarang pun tetap saja menarik. Barangkali, bisa dikatakan, banyaknya simpati serta dukungan rakyat yang dicurahkan kepada PDI Perjuangan karena adanya ketidakadilan penguasa dalam memperlakukan Megawati dengan PDI Perjuangannya. Contoh paling mencolok adalah pada Peristiwa 27 Juli 1996 berupa penyerangan ke kantor PDI. Untunglah peristiwa ini sama sekali tidak membuat Megawati dan pengikutnya gentar. Mereka terus berjuang; bahkan, sejak itu, nama Megawati makin melambung dan mendapat simpati dari berbagai kalangan.
Dilihat dari pribadi Mbak Mega sendiri, beliau bukan seorang yang emosional; juga bukan seorang politisi yang mabok. Jadi bukan hal yang aneh kalau saya memberi kesempatan serta dukungan kepada beliau untuk memimpin negeri tercinta ini. Selamat berjuang!
TYUD TAHYUDDIN, Majalah PANJI MASYARAKAT dan TOKOH
Walaupun belum pernah bertemu langsung, saya berani berspekulasi, bahwa Mbak Mega itu orang yang bersahaja, lembut dan bijaksana. Terus terang, dari senyumnya yang menawan, saya menarik kesan dia orang yang simpatik. Gaya bertutur katanya pun sangat keibuan. Soal Mega anak Bung Karno, bagi saya kok suatu hal yang kebetulan semata.
Sebagai Ketua Umum sebuah partai politik yang besar dan calon pemimpin negeri ini, tampak sepadan dengan kekuatan kharisma dan kewibawaannya. Terlepas dari simpang siur opini tentang beliau, saya tetap mengagumi Megawati sebagai figur yang fenomenal, tabah dan tegar.
Meskipun upaya menjegal langkahnya sangat deras dan datang dari berbagai penjuru, namun dengan semangat dan dukungan para simpatisannya, akhirnya Megawati membawa PDI Perjuangan ke peringkat pertama perolehan suara dalam Pemilu 1999. Sebuah prestasi yang sangat mencengangkan!
DIDIE SW, Tabloid AKSI
Dalam situasi tertentu, sebut saja pada saat terjadi demo atau unjuk rasa, kartun juga cukup berperan untuk menjadi alat penyampai pesan atau visi. Mungkin hanya berupa coretan sederhana, namun bila dicermati ia cukup efektif untuk menyampaikan keperluan itu. Kalau dilihat secara teknis saja ujudnya memang kartun/karikatur, tetapi fungsinya toh tetap saja sebagai alat penyampai pesan atau seperti pamflet/poster. Jadi, jangan buru-buru dibingungkan dengan karikatur yang dimuat di koran/majalah.
Nah, soal contoh gambar kartun yang digunakan untuk demo, buktinya dapat dilihat dari berbagai unjuk rasa yang ditayangkan di televisi maupun dimuat di surat kabar dan majalah. Salah satu contoh yang gampang diingat, yaitu ketika para mahasiswa hendak memprotes Kejagung karena kinerjanya dalam mengusut kasus KKN dinilai lamban/pengecut; mereka berunjuk rasa ke Gedung Bundar sambil memajang gambar kartun Andi M. Ghalib berbadan ayam betina di setiap dinding kejaksaan. Cukup menggelitik, bukan?
Di sisi lain, kartun/karikatur juga cukup ampuh untuk mengekspresikan gagasan kita tentang sesuatu yang tidak terduga. Suatu saat saya pernah mengadakan semacam “eksperimen” dengan cara menggambar karikatur Megawati dalam figur seorang Superman. Gagasan ini dilandasi pemikiran bahwa Mega, kendati seorang wanita, memiliki kans yang super untuk menjadi presiden negeri ini atau wanita super yang mampu membuat histeria massa pendukungnya.
Tetapi apa yang terjadi? Ternyata massa PDI Perjuangan sendiri menolak penggambaran itu. Alasannya, gender. Mega adalah wanita dan Superman adalah laki-laki. Persoalan itu harus jelas dulu. Soal potensi dan kemampuannya bisa menyamai Superman, mengapa tidak ditampilkan dalam bentuk Wonder Woman, misalnya? Mungkin yang terpikir di benak mereka begitu. Reaksi pembaca itu, cukup mengagetkan saya, kendati sebenarnya masuk akal. Namun sebagian yang lain mengatakan, bahwa yang super itu cuma satu, yaitu Tuhan.
Itulah pengalaman yang pernah saya alami; tak kurang dari surat-surat kritik yang dikirim pembaca dan telepon yang memaki-maki dengan kata-kata kasar, pernah mengisi kenangan hidup saya selama menjalani profesi sebagai karikaturis. Pelajaran yang bisa dipetik dari peristiwa itu adalah, “Karya karikatur sebenarnya selalu terbuka untuk multiinterpretasi, namun kesalahpahaman bisa berakibat yang lebih tidak lucu dari karikaturnya sendiri.”
JOKO SUSILO, Harian SUARA MERDEKA
Salut atas keberanian Megawati, walaupun dihalang-halangi berbagai rintangan, dia akan terus melangkah. Mega tampaknya ingin membentuk proses demokrasi yang sejalan dengan hati nurani rakyat; dan itu dia tunjukkan dengan tanpa banyak bicara.
Pada prinsipnya saya senang-senang saja jika Mbak Mega benar-benar menjadi presiden negeri ini, paling tidak saya bisa menyebut beliau Mbak Presiden; eh, maksud saya agar proses demokratisasi berjalan sesuai dengan kehendak rakyat banyak. Sebaiknya beri dia kesempatan untuk membuktikan diri bahwa Mega mampu berbuat optimal untuk bangsa ini.
Soal diamnya Mega, mungkin itu cara dia untuk menunjukkan kecerdasan dan kualitasnya sebagai calon pemimpin bangsa agar tidak terkesan mudah goyah dan emosional. Seseorang meyakini sesuatu tentu ada alasannya.
Kita semua menunggu, Mbak Mega membuktikan bahwa dirinya mampu menjadi pemimpin bangsa. Selain itu kita juga menunggu bukti komitmennya untuk memberantas KKN yang nyata-nyata merusak mental bangsa ini. Selamat atas kemenangan PDI Perjuangan, yang berarti juga kemenangan Mbak Mega.
LIBRA (RAHMAT RIYADI), Majalah Berita Mingguan GATRA
Diam itu mas? No!! Diam itu Mbak Mega!!
GESIGORAN, Harian BERITA BUANA
Saya hanya punya tiga kata untuk menggambarkan sosok Mega: Tenang, Tegar dan Tabah.
M. SYAIFUDIN IFOED, Tabloid BIANGLALA
“Jika ada rasa dendam secuil pun dalam sanubariku itu akan meracuni nuraniku,” ucap Mega. Di balik sosoknya yang lembut dan keibuan ternyata menyimpan kekuatan moral yang luhur dan tulus. Adis – panggilan Megawati Soekarnoputri adalah Srikandi yang lahir di abad ini dan siap menghujamkan anak panahnya demi lancarnya proses demokrasi dan reformasi di negeri ini.
Keyakinannya bahwa “Kebenaran yang akan menang” membuat Mega menjadi figur pimpinan yang sangat dirindukan rakyatnya. Ketika menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan, ia mendapat ujian yang sangat berat. Ketenaran dan popularitasnya juga tidak datang begitu saja; tetapi melalui perjuangan dan liku yang bukan main rumitnya. Hujatan, tekanan dan penganiayaan politik dihadapi Mega dengan sabar, tabah, tegar, dan tidak mendendam.
Sepantasnyalah bila Mega menjadi simbol “perlawanan” terhadap pemimpin Orde Baru yang selama ini berkuasa terlalu lama dan penuh dengan sandiwara politik. Walaupun mendapat dukungan arus bawah cukup besar, perjalanan politik Mega tidak juga berjalan mulus. Pencalonan Megawati sebagai salah satu calon pemimpin bangsa ini banyak mendapat ganjalan dari kalangan elit politik.
Tampaknya, kehadiran seorang perempuan menjadi pemimpin negara masih menjadi polemik ramai. Untuk mengubah tradisi politik di Indonesia menuju alam pikiran yang demokratis, perlu ada tenggang waktu untuk berlatih dan memperlancar diri; karena memang tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Dan Mega terus melaju, rakyat tak ragu mendukung langkahnya. Gerak langkah Mega telah tercatat dalam sejarah perjalanan bangsa ini, dengan sangat fenomenal. Kenapa dengan Mega? Kenapa kita takut pada perubahan? Bukankah perubahan itu terjadi setiap hari, setiap jam bahkan setiap menit dan detik. Perubahan itu terjadi secara alami kata Dyah Megawati Soekarnoputri.
PUTU SUARIA SOETHAMA (TUSUARIA), Bali Sekala Advertising
“Megawati adalah sebuah garis lurus”; sisi lengkungnya dari kacamata saya sebagai kartunis belum saya temui sejak Orba hingga Orde Reformasi.
GATOT EKO CAHYONO, Harian Sore SUARA PEMBARUAN
Megawati itu ibarat seorang yang telah siap untuk “ menuai “ apa yang telah ditanamnya. Beliau “menanam” dengan ketulusan hati, kegigihan, dan tahan banting selama bertahun–tahun di dalam partainya. Batu sandungan dan rintangan, beliau lalui dengan tabah dan tak gentar.
Kalaupun akhir–akhir ini beliau dicap figur yang “diam” terutama dalam menyikapi kemenangan perolehan suara PDI Perjuangan pada Pemilu ’99 bukan berarti beliau cuek. Saya yakin beliau akan “action” setelah semuanya jelas dan pasti. Karena hal ini bukan semata–mata kepentingan partai, tetapi juga kepentingan negara dan bangsa.
FUAD T. ABIDIN, (d/h MAJALAH SINAR)
Andaikata Megawati Soekarnoputri bernama Megawanto Soekarnoputra dan berkelamin laki-laki, mungkin suasana perpolitikan Indonesia tidak akan seuring-uringan sekarang ini. Tapi kenyataan yang ada membuat orang-orang menjadi bertingkah aneh. Ujung-ujungnya membuat masyarakat yang berharap bahwa setelah Pemilu, kondisi sosial, politik, ekonomi Indonesia akan membaik, menjadi ragu-ragu; jangan-jangan nanti malah terjadi perpecahan di dalam masyarakat.
Pemilu telah berakhir dan dari hasil penghitungan suara, kecen¬derungan PDI Perjuangan yang dipimpin Megawati akan memenangkan Pemilu telah jelas. PDI Perjuangan mendapat kemenangan dengan jumlah suara yang fantastis di sebagian besar wilayah Indonesia. Angka-angka pero¬lehan suaranya membuat orang seakan tak percaya bahwa partai itu adalah partai yang dulunya begitu sering diobok-obok oleh pemerintahan Orde Baru; yakni agar terus terjadi konflik dan keributan, sehingga timbul kesan PDI pimpinan Megawati itu, payah.
PDI Perjuangan dengan Megawatinya begitu fenomenal, sehingga ada kekhawatiran bahwa kemenangan itu hanyalah buah dari pelampiasan emosi rakyat semata dan tidak didasarkan atas pertimbangan rasional. Mengingat figur Soekarno sangat melekat padanya dan mungkin romantisme dari pendukung Soekarno dahulu seakan mendapatkan pelipur lara dalam diri Megawati. Mungkin ada benarnya kalau Megawati menjadi sangat diidolakan oleh pendukungnya. Megawati dan PDI Perjuangan dianggap sebagai simbol dari ketertindasan rakyat oleh pemerintahan Orde Baru.
Salah satu peristiwa penindasan yang sulit dilupakan antara lain kasus 27 Juli 1996. PDI Perjuangan yang terbuka bagi setiap golongan masyarakat menjadi pelarian bagi orang-orang yang kecewa terhadap Orde Baru dan Golkar. Masyarakat menginginkan pemimpin yang menjadi pengayom mereka, dan Megawati dianggap sebagai figur yang pas.
Tetapi permasalahan tidak berhenti sampai di sini. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat majemuk; dan pengaruh Orde Baru masih sangat erat melekat dalam pola pikir mereka. Ditambah lagi dengan umat Islam sebagai golongan terbesar di Indonesia dan kesensitifan mereka terhadap masalah gender, menjadikan posisi Megawati sebagai calon kuat presiden Indonesia, terkesan kurang mulus.
Buat saya pribadi, sekarang belum saatnya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang demokratis. Kenyataan membukti¬kan bahwa Pemilu sebagai perangkat demokrasi yang jelas mene¬lorkan PDI Perjuangan sebagai pemenang tidak otomatis membuat Megawati menjadi presiden. Sebab masyarakat tidak memilih presiden secara langsung tetapi memilih wakil untuk duduk di MPR yang akan memilih presiden. Celah itu yang akan menjadi ganjalan bagi Megawati. Isu itu menjadi pemicu derasnya keinginan untuk kembali menyetel ulang UUD 45 lewat jalan amandemen. Masalah gender dan dikotomi muslim-nonmuslim juga menjadi persoalan yang unik dalam menuju masyarakat yang demokratis tersebut.
Tentu saja persoalan bukan tidak ada pemecahannya. Bisa saja Megawati tidak mencalonkan diri sebagai presiden tetapi diganti¬kan dengan figur lain yang bisa diterima masyarakat keseluruhan. Tetapi, bukan itu persoalannya. Reformasi bertujuan agar peruba¬han terjadi pada masyarakat Indonesia. Selama ini kita sudah terbiasa untuk mengangguk-angguk saja bila ada kebijakan baru pemerintah meskipun akhirnya merugikan masyarakat. Kita harus merubah gerakan anggukan kepala kita menjadi menggeleng-geleng tanda tak harus setuju terhadap kebijakan baru pemerintah, agar pemerintah mau mendengarkan dulu keinginan masyarakat banyak.
Perlu ada pembelajaran demokrasi pada masyarakat kita. Selama ini kita telah terbiasa pada pola paternalistik yang segala sesuatunya ditentukan oleh pihak yang berkuasa. Berkembangnya situasi yang menempatkan sistem sebagai pilar utama penyangga demokrasi di negeri ini, memungkinkan kita untuk tidak harus selalu melihat figur pimpinan sebagai satu-satunya rujukan dalam memutuskan sesuatu.
Untuk itu diperlukan pemimpin yang mampu berperilaku demokra¬tis, mau berdialog, berdebat, dan menghargai pendapat orang lain. Dari sana diharapkan perilaku itu akan berkembang menjadi sebuah tradisi demokrasi oleh seluruh rakyat kita.
Saya percaya Megawati bisa. Dan saya juga percaya pada ucapannya bahwa dia akan menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Dari sini diharapkan bahwa semua bidang akan dikelola secara profesional. Termasuk bidang hukum yang menjadi penopang tegaknya demokrasi. Tetapi bila Megawati tidak terpilih, setidaknya dia telah menunjukkan bahwa kekuatan riil masyarakat mampu untuk mengalahkan "kekuatan semu" Orde Baru. Dia bisa menjadi simbol bagi perlawanan dengan diam terhadap penindasan; seperti perlawanan diamnya Gandhi pada penindasan Inggris atas India. Saya tidak tahu pendapat saya ini benar atau salah. Soalnya, Megawati tidak pernah berbicara kepada saya. Peace !!!